Pelajaran Ilmu Manthiq (Logika) Untuk Pemula
Definisi dan Urgensi Mantiq
Mantiq adalah alat atau dasar yang penggunaannya akan menjaga kesalahan
dalam berpikir.
Lebih jelasnya, Mantiq adalah sebuah ilmu yang membahas tentang alat dan
formula berpikir, sehingga seseorang yang menggunakannya akan selamat
dari cara berpikir salah.
Manusia sebagai makhluk yang berpikir tidak akan lepas dari berpikir.
Namun, saat berpikir, manusia seringkali dipengaruhi oleh berbagai
tendensi, emosi, subyektifitas dan lainnya sehingga ia tidak dapat
berpikir jernih, logis dan obyektif. Mantiq merupakan upaya agar
seseorang dapat berpikir dengan cara yang benar, tidak keliru.
Sebelum kita pelajari masalah-masalah mantiq, ada baiknya kita
mengetahui apa yang dimaksud dengan “berpikir”.
Berpikir adalah proses pengungkapan sesuatu yang misteri (majhul atau
belum diketahui) dengan mengolah pengetahuan-pengetahuan yang telah ada
dalam benak kita (dzihn) sehingga yang majhul itu menjadi ma’lûm
(diketahui).
Faktor-Faktor Kesalahan Berpikir 1. Hal-hal yang dijadikan dasar
(premis) tidak benar. 2. Susunan atau form yang menyusun premis tidak
sesuai dengan kaidah mantiq yang benar.
Argumentasi (proses berpikir) dalam alam pikiran manusia bagaikan sebuah
bangunan. Suatu bangunan akan terbentuk sempurna jika tersusun dari
bahan-bahan dan konstruksi bangunan yang sesuai dengan teori-teori yang
benar. Apabila salah satu dari dua unsur itu tidak terpenuhi, maka
bangunan tersebut tidak akan terbentuk dengan baik dan sempurna. Sebagai
misal, “[1] Socrates adalah manusia; dan [2] setiap manusia bertindak
zalim; maka [3] Socrates bertindak zalim”. Argumentasi semacam ini benar
dari segi susunan dan formnya. Tetapi, salah satu premisnya salah yaitu
premis yang berbunyi “Setiap manusia bertindak zalim”, maka konklusinya
tidak tepat. Atau misal, “[1] Socrates adalah manusia; dan [2] Socrates
adalah seorang ilmuwan”, maka “[3] manusia adalah ilmuwan”. Dua premis
ini benar tetapi susunan atau formnya tidak benar, maka konklusinya
tidak benar. (Dalam pembahasan qiyas nanti akan dijelaskan susunan
argumentasi yang benar, pen).
Ilmu dan Idrak
Dua kata di atas, Ilmu dan Idrak, mempunyai makna yang sama (sinonim).
Dalam ilmu mantiq, kedua kata ini menjadi bahasan yang paling penting
karena membahas aspek terpenting dalam pikiran manusia, yakni ilmu. Oleh
karena itu, makna ilmu sendiri perlu diperjelas. Para ahli mantiq
(mantiqiyyin) mendefinisikan ilmu sebagai berikut:
Ilmu adalah gambaran tentang sesuatu yang ada dalam benak (akal). Benak
atau pikiran kita tidak lepas dari dua kondisi yang kontradiktif, yaitu
ilmu dan jahil (ketidak tahuan). Pada saat keluar rumah, kita
menyaksikan sebuah bangunan yang megah dan indah, dan pada saat yang
sama pula tertanam dalam benak gambaran bangunan itu. Kondisi ini
disebut “ilmu”. Sebaliknya, sebelum menyaksikan bangunan tersebut, dalam
benak kita tidak ada gambaran itu. Kondisi ini disebut “jahil”.
Pada kondisi ilmu, benak atau akal kita terkadang hanya [1] menghimpun
gambaran dari sesuatu saja (bangunan, dalam misal). Terkadang kita tidak
hanya menghimpun tetapi juga [2] memberikan penilaian atau hukum
(judgement). (Misalnya, bangunan itu indah dan megah). Kondisi ilmu yang
pertama disebut tashawwur dan yang kedua disebut tashdiq. Jadi tashawwur
hanya gambaran akan sesuatu dalam benak. Sedangkan tashdiq adalah
penilaian atau penetapan dengan dua ketetapan: “ya” atau “tidak/bukan”.
Misalnya, “air itu dingin”, atau “air itu tidak dingin”; “manusia itu
berakal”, atau “manusia itu bukan binatang” dan lain sebagainya.
Kesimpulan, ilmu dibagi menjadi dua; tashawwuri dan tashdiqi.
Dharuri dan Nadzari
Ilmu tashawwuri dan ilmu tashdiqi mempunyai dua macam: dharuri dan
nadzari. Dharuri adalah ilmu yang tidak membutuhkan pemikiran lagi
(aksiomatis). Nadzari adalah ilmu yang membutuhkan pemikiran.
Lebih jelasnya, dharuri (sering juga disebut badihi) adalah ilmu dan
pengetahuan yang dengan sendirinya bisa diketahui tanpa membutuhkan
pengetahuan dan perantaraan ilmu yang lain. Jadi Ilmu tashawwuri dharuri
adalah gambaran dalam benak yang dipahami tanpa sebuah proses pemikiran.
Contoh: 2 x 2 = 4; 15 x 15 = 225 atau berkumpulnya dua hal yang
kontradiktif adalah mustahil (tidak mungkin terjadi) adalah hal yang
dharuri. Sedangkan nadzari dapat diketahui melalui sebuah proses
pemikiran atau melalui pengetahuan yang sudah diketahui sebelumnya.
(Lihat kembali definisi berpikir). Jadi ilmu tashawwuri nadzari adalah
gambaran yang ada dalam benak yang dipahami melalui proses pemikiran.
Contoh: bumi itu bulat adalah hal yang nadzari.
Kulli dan Juz’i
Pembahasan tentang kulli (general) dan juz’i (parsial) secara esensial
sangat erat kaitannya dengan tashawwur dan juga secara aksidental
berkaitan dengan tashdiq.
Kulli adalah tashawwur (gambaran benak) yang dapat diterapkan (berlaku)
pada beberapa benda di luar. Misalnya: gambaran tentang manusia dapat
diterapkan (berlaku) pada banyak orang; Budi, Novel, Yani dan lainnya.
Juz’i adalah tashawwur yang dapat diterapkan (berlaku) hanya pada satu
benda saja.
Misalnya: gambaran tentang Budi hanya untuk seorang yang bernama Budi
saja. Manusia dalam berkomunikasi tentang kehidupan sehari-hari
menggunakan tashawwur-thasawwur yang juz’i. Misalnya: Saya kemarin ke
Jakarta; Adik saya sudah mulai masuk sekolah; Bapak saya sudah pensiun
dan sebagainya. Namun, yang dipakai oleh manusia dalam kajian-kajian
keilmuan adalah tashawwur-thasawwur kulli, yang sifatnya universal.
Seperti: 2 x 2 = 4; Orang yang beriman adalah orang bertanggung jawab
atas segala perbuatannya; Setiap akibat pasti mempunyai sebab dan lain
sebagainya. Dalam ilmu mantiq kita akan sering menggunakan kulli
(gambaran-gambaran yang universal), dan jarang bersangkutan dengan juz’i.
Nisab Arba’ah
Dalam benak kita terdapat banyak tashawwur yang bersifat kulli dan
setiap yang kulli mempunyai realita (afrad) lebih dari satu. (Lihat
definisi kulli ). Kemudian antara tashawwur kulli yang satu dengan yang
lain mempunyai hubungan (relasi). Ahli mantiq menyebut bentuk hubungan
itu sebagai “Nisab Arba’ah”. Mereka menyebutkan bahwa ada empat kategori
relasi: [1] Tabâyun (diferensi), [2] Tasâwi (ekuivalensi), [3] Umum wa
khusus Mutlaq (implikasi) dan [4] Umum wa Khusus Minwajhin (asosiasi).
1. Tabâyun adalah dua tashawwur kulli yang masing-masing dari keduanya
tidak bisa diterapkan pada seluruh afrad tashawwur kulli yang lain.
Dengan kata lain, afrad kulli yang satu tidak mungkin sama dan
bersatu dengan afrad kulli yang lain. Misal: tashawwur manusia dan
tashawwur batu. Kedua tashawwur ini sangatlah berbeda dan afradnya
tidak mungkin sama. Setiap manusia pasti bukan batu dan setiap batu
pasti bukan manusia.
2. Tasâwi adalah dua tashawwur kulli yang keduanya bisa diterapkan pada
seluruh afrad kulli yang lain. Misal: tashawwur manusia dan
tashawwurt berpikir. Artinya setiap manusia dapat berpikir dan
setiap yang berpikir adalah manusia.
3. Umum wa khusus mutlak adalah dua tashawwur kulli yang satu dapat
diterapkan pada seluruh afrad kulli yang lain dan tidak sebaliknya.
Misal: tashawwur hewan dan tashawwur manusia. Setiap manusia adalah
hewan dan tidak setiap hewan adalah manusia. Afrad tashawwur hewan
lebih umum dan lebih luas sehingga mencakup semua afrad tashawwur
manusia.
4. Umum wa khusus min wajhin adalah dua tashawwur kulli yang
masing-masing dari keduanya dapat diterapkan pada sebagian afrad
kulli yang lain dan sebagian lagi tidak bisa diterapkan. Misal:
tashawwur manusia dan tashawwur putih. Kedua tashawwur kulli ini
bersatu pada seorang manusia yang putih, tetapi terkadang keduanya
berpisah seperti pada orang yang hitam dan pada kapur tulis yang putih.
Hudud dan Ta’rifat
Kita sepakat bahwa masih banyak hal yang belum kita ketahui (majhul).
Dan sesuai dengan fitrah, kita selalu ingin dan mencari tahu tentang
hal-hal yang masih majhul.
Pertemuan lalu telah dibahas bahwa manusia memiliki ilmu dan pengetahuan
(ma’lûm), baik tashawwuri ataupun tashdiqi. Majhul (jahil) sebagai
anonim dari ma’lûm (ilmu), juga terbagi menjadi dua majhul tashawwuri
dan majhul tashdiqi. Untuk mengetahui hal-hal majhul tashawwuri, kita
membutuhkan ma’lûm tashaswwuri. (Lihat definisi berpikir. Pencarian
majhul tashawwur dinamakan “had” atau “ta’rif”.
Had/ta’rif adalah sebuah jawaban dan keterangan yang didahului
pertanyaan “Apa?”.
Saat menghadapi sesuatu yang belum kita ketahui (majhul), kita akan
segara bertanya “apa itu?”. Artinya, kita bertanya tentang esensi dan
hakikat sesuatu itu. Jawaban dan keterangan yang diberikan adalah had
(definisi) dari sesuatu itu.
Oleh karena itu, dalam disiplin ilmu, mendefinisikan suatu materi yang
akan dibahas penting sekali sebelum membahas lebih lanjut
masalah-masalah yang berkaitan dengannya. Perdebatan tentang sesuatu
materi akan menjadi sia-sia kalau definisinya belum jelas dan
disepakati. Ilmu mantiq bertugas menunjukkan cara membuat had atau
definisi yang benar.
Macam-Macam Definisi (Ta’rif)
Setiap definisi bergantung pada kulli yang digunakan. Ada lima kulli
yang digunakan untuk mendefinisikan majhul tashawwuri (biasa disebut
“kulliyat khamsah”). Lima kulli itu adalah: [1] Nau’ (spesies), [2] jins
(genius), [3] fashl (diferentia), [4] ‘aradh ‘aam (common accidens) dan
[5] ‘aradh khas (proper accidens). Pembahasan tentang kulliyat khamsah
ini secara detail termasuk pembahasan filsafat, bukan pembahasan mantiq.
1. Had Tâm, adalah definisi yang menggunakan jins dan fashl untuk
menjelaskan bagian-bagian dari esensi yang majhul. Misal: Apakah
manusia itu? Jawabannya adalah “Hewan yang berpikir (natiq)”.
“Hewan” adalah jins manusia, dan “berpikir” adalah fashl manusia.
Keduanya merupakan bagian dari esensi manusia.
2. Had Nâqish, adalah definisi yang menggunakan jins saja. Misal:
“Manusia adalah hewan”. Hewan adalah salah satu dari esensi manusia.
3. Rasam Tâm, adalah definisi yang mengunakan ‘ardh khas. Misal:
“Manusia adalah wujud yang berjalan, tegak lurus dan dapat tertawa”.
“Maujud yang berjalan”, “tegak lurus” dan “tertawa” bukan bagian
dari esensi manusia, tetapi hanya bagian yang eksiden.
4. Rasam Nâqish, adalah definisi yang menggunakan ‘ardh ‘âm, misalnya,
“Manusia adalah wujud yang berjalan”.
Qadhiyyah (Proposisi)
Sebagaimana yang telah kita ketahui, tashdiqi adalah penilaian dan
penghukuman atas sesuatu dengan sesuatu yang lain (seperti: gunung itu
indah; manusia itu bukan kera dan lain sebagainya). Atas dasar itu,
tashdiq berkaitan dengan dua hal: maudhu’ dan mahmul (“gunung” sebagai
maudhu’ dan “indah” sebagai mahmul). Gabungan dari dua sesuatu itu
disebut qadhiyyah (proposisi).
Macam-macam Qadhiyyah
Setiap qadhiyyah terdiri dari tiga unsur: 1) mawdhu’, 2) mahmul dan 3)
rabithah (hubungan antara mawdhu’ dan mahmul). Berdasarkan masing-masing
unsur itu, qadhiyyah dibagi menjadi beberapa bagian.
Berdasarkan rabithah-nya, qadhiyyah dibagi menjadi dua: hamliyyah
(proposisi kategoris) dan syarthiyyah (proposisi hipotesis).
Qadhiyyah hamliyyah adalah qadhiyyah yang terdiri dari mawdhu’, mahmul
dan rabithah.
Lebih jelasnya, ketika kita membayangkan sesuatu, lalu kita menilai atau
menetapkan atasnya sesuatu yang lain, maka sesuatu yang pertama disebut
mawdhu’ dan sesuatu yang kedua dinamakan mahmul dan yang menyatukan
antara keduanya adalah rabithah. Misalnya: “gunung itu indah”. “Gunung”
adalah mawdhu’, “indah” adalah mahmul dan “itu” adalah rabithah
(Qadhiyyah hamliyyah, proposisi kategorik)
Terkadang kita menafikan mahmul dari mawdhu’. Misalnya, “gunung itu
tidak indah”. Yang pertama disebut qadhiyyah hamliyyah mujabah
(afirmatif) dan yang kedua disebut qadhiyyah hamliyyah salibah (negatif).
Qadhiyyah syarthiyyah terbentuk dari dua qadhiyyah hamliyah yang
dihubungkan dengan huruf syarat seperti, “jika” dan “setiap kali”.
Contoh: jika Tuhan itu banyak, maka bumi akan hancur. “Tuhan itu banyak”
adalah qadhiyyah hamliyah; demikian pula “bumi akan hancur” sebuah
qadhiyyah hamliyah. Kemudian keduanya dihubungkan dengan kata “jika”.
Qadhiyyah yang pertama (dalam contoh, Tuhan itu banyak) disebut muqaddam
dan qadhiyyah yang kedua (dalam contoh, bumi akan hancur) disebut tali.
Qadhiyyah syarthiyyah dibagi menjadi dua: muttasilah dan munfasilah.
Qadhiyyah syarthiyyah yang menggabungkan antara dua qadhiyyah seperti
contoh di atas disebut muttasilah, yang maksudnya bahwa adanya
“keseiringan” dan “kebersamaan” antara dua qadhiyyah. Tetapi qadhiyyah
syarthiyyah yang menunjukkan adanya perbedaan dan keterpisahan antara
dua qadhiyyah disebut munfasilah, seperti, Bila angka itu genap, maka ia
bukan ganjil. Antara angka genap dan angka ganjil tidak mungkin kumpul.
Qadhiyyah Mahshurah dan Muhmalah
Pembagian qadhiyyah berdasarkan mawdhu’-nya dibagi menjadi dua:
mahshurah dan muhmalah. Mahshurah adalah qadhiyyah yang afrad (realita)
mawdhu’-nya ditentukan jumlahnya (kuantitasnya) dengan menggunakan kata
“semua” dan “setiap” atau “sebagian” dan “tidak semua”. Contohnya, semua
manusia akan mati atau sebagian manusia pintar. Sedangkan dalam muhmalah
jumlah afrad mawdhu’-nya tidak ditentukan. Contohnya, manusia akan mati,
atau manusia itu pintar.
Dalam ilmu mantiq, filsafat, eksakta dan ilmu pengetahuan lainnya,
qadhiyyah yang dipakai adalah qadhiyyah mahshurah.
Qadhiyyah mahshurah terkadang kulliyah (proposisi determinatif general)
dan terkadang juz’iyyah (proposisi determinatif partikular) dan
qadhiyyah sendiri ada yang mujabah (afirmatif) dan ada yang salibah
(negatif) . Maka qadhiyyah mahshurah mempunyai empat macam:
1. Mujabah kulliyyah: Setiap manusia adalah hewan
2. Salibah kulliyyah: Tidak satupun manusia yang berupa batu.
3. Mujabah juz’iyyah: Sebagian manusia pintar
4. Salibah juz’iyyah: Sebagian manusia bukan laki-laki.
Sebenarnya masih banyak lagi pembagian qadhiyyah baik berdasarkan
mahmul-nya (qadhiyyah muhassalah dan mu’addlah), atau jihat qadhiyyah
(dharuriyyah, daimah dan mumkinah) dan qadhiyyah syarthiyyah muttasilah
(haqiqiyyah, maani’atul jama’ dan maani’atul khulw). Namun qadhiyyah
yang paling banyak dibahas dalam ilmu filsafat, mantiq dan lainnya
adalah qadhiyyah mahshurah.
Hukum-Hukum Qadhiyyah
Setelah kita ketahui definisi dan pembagian qadhiyyah, maka pembahasan
berikutnya adalah hubungan antara masing-masing dari empat qadhiyyah
mahshurah. Pada pembahasan terdahulu telah kita ketahui bahwa terdapat
empat macam hubungan antara empat tashawwuri kulli: [1] tabâyun, [2]
tasâwi, [3] umum wa khusus mutlak dan [4] umum wa khusus min wajhin.
Demikian pula terdapat empat macam hubungan antara masing-masing empat
qadhiyyah mahshurah: [1] tanaqudh, [2] tadhadd, [3] dukhul tahta tadhadd
dan [4] tadakhul.
1. Tanaqudh (mutanaqidhain [kontradiktif]) adalah dua qadhiyyah yang
mawdhu’ dan mahmul-nya sama, tetapi kuantitas (kam) dan kualitasnya
(kaif) berbeda, yakni yang satu kulliyah mujabah dan yang lainnya
juz’iyyah salibah. Misalnya, “Semua manusia hewan” (kulliyyah
mujabah) dengan “Sebagian manusia bukan hewan” (juz’iyyah salibah).
2. Tadhad (kontrariatif) adalah dua qadhiyah yang sama kuantitasnya
(keduanya kulliyyah), tetapi yang satu mujabah dan yang lain
salibah. Misalnya, “Semua manusia dapat berpikir” (kulliyyah
mujabah) dengan “Tidak satupun dari manusia dapat berpikir”
(kulliyyah salibah).
3. Dukhul tahta tadhad (dakhilatain tahta tadhad [interferensif
sub-kontrariatif]) adalah dua qadhiyyah yang sama kuantitasnya
(keduanya juz’iyyah), tetapi yang satu mujabah dan lain salibah.
Misalnya: “Sebagian manusia pintar” (juz’iyyah mujabah) dengan
“Sebagian manusia tidak pintar” (juz’iyyah salibah).
4. Tadakhul (mutadakhilatain [interferensif]) adalah dua qadhiyyah yang
sama kualitasnya tetapi kuantitasnya berbeda. Misalnya: “Semua
manusia akan mati” (kulliyyah mujabah) dengan “Sebagian manusia akan
mati” (juz’iyyah mujabah) atau “Tidak satupun dari manusia akan
kekal” (kulliyyah salibah) dengan “Sebagian manusia tidak kekal”
(juz’iyyah salibah). Dua qadhiyyah ini disebut pula
Hukum dua qadhiyyah mutanaqidhain (kontradiktif) jika salah satu dari
dua qadhiyyah itu benar, maka yang lainnya pasti salah. Demikian pula
jika yang satu salah, maka yang lainnya benar. Artinya tidak mungkin
(mustahil) keduanya benar atau keduanya salah. Dua qadhiyyah biasa
dikenal dengan ijtima’ al naqidhain mustahil (kombinasi kontradiktif).
Hukum dua qadhiyyah mutadhaddain (kontrariatif), jika salah satu dari
dua qadhiyyah itu benar, maka yang lain pasti salah. Tetapi, jika salah
satu salah, maka yang lain belum tentu benar. Artinya keduanya tidak
mungkin benar, tetapi keduanya mungkin salah.
Hukum dua qadhiyyah dakhlatain tahta tadhad (interferensif
sub-kontrariatif), jika salah satu dari dua qadhiyyah itu salah, maka
yang lain pasti benar. Tetapi, jika yang satu benar, maka yang lain
belum tentu salah. Dengan kata lain, kedua qadhiyyah itu tidak mungkin
salah, tetapi mungkin saja keduanya benar.
Hukum dua qadhiyyah mutadakhilatain (interferentif), berbeda dengan
masalah tashawwuri. (Lihat pembahasan tentang nisab arba’ah, pen); bahwa
tashawwur kulli (misalnya, manusia) lebih umum dari tashawwur juz’i
(misalnya, Ali). Di sini, qadhiyyah kulliyyah lebih khusus dari
qadhiyyah juz’iyyah. Artinya, jika qadhiyyah kulliyyah benar, maka
qadhiyyah juz’iyyah pasti benar.
Tetapi, jika qadhiyyah juz’iyyah benar, maka qadhiyyah kulliyyah belum
tentu benar. Misalnya, jika “setiap A adalah B” (qadhiyyah kulliyyah),
maka pasti “sebagian A pasti B”. Tetapi jika “sebagian A adalah B”, maka
belum pasti “setiap A adalah B”.
Tanaqudh
Salah satu hukum qadhiyyah yang menjadi dasar semua pembahasan mantiq
dan filsafat adalah hukum tanaqudh (hukum kontradiksi). Para ahli mantiq
dan filsafat menyebutkan bahwa selain mawdhu’ dan mahmul dua qadhiyyah
mutanaqidhain itu harus sama, juga ada beberapa kesamaan dalam kedua
qadhiyyah tersebut. Kesamaan itu terletak pada:
1. Kesamaan tempat (makan)
2. Kesamaan waktu (zaman)
3. Kesamaan kondisi (syart)
4. Kesamaan korelasi (idhafah)
5. Kesamaan pada sebagian atau keseluruhan (juz dan kull )
6. Kesamaan dalam potensi dan aktual (bil quwwah dan bil fi’li). Qiyas
(silogisme)
Pembahasan tentang qadhiyyah sebenarnya pendahuluan dari masalah qiyas,
sebagaimana pembahasan tentang tashawwur sebagai pendahuluan dari hudud
atau ta’rifat. Dan sebenarnya inti pembahasan mantiq adalah hudud dan qiyas.
Qiyas adalah kumpulan dari beberapa qadhiyyah yang berkaitan yang jika
benar, maka dengan sendirinya (li dzatihi) akan menghasilkan qadhiyyah
yang lain (baru).
Sebelum kita lebih lnjut membahas tentang qiyas, ada baiknya kita secara
sekilas beberapa macam hujjah (argumentasi ). Manusia disaat ingin
mengetahui hal-hal yang majhul, maka terdapat tiga cara untuk mengetahuinya:
1. Pengetahuan dari juz’i ke juz’i yang lain. Argumenatsi ini sifatnya
horisontal, dari sebuah titik yang parsial ke titik parsial lainnya.
Argumentasi ini disebut tamtsil (analogi).
2. Pengetahuan dari juz’i ke kulli. Atau dengan kata lain, dari khusus
ke umum (menggeneralisasi yang parsial) Argumentasi ini bersifat
vertikal, dan disebut istiqra’ (induksi).
3. Pengetahuan dari kulli ke juz’i. Atau dengan kata lain, dari umum ke
khusus. Argumentasi ini disebut qiyas (silogisme).
Macam-macam Qiyas
Qiyas dibagi menjadi dua; iqtirani (silogisme kategoris) dan istitsna’i
(silogisme hipotesis). Sesuai dengan definisi qiyas di atas, satu
qadhiyyah atau beberapa qadhiyyah yang tidak dikaitkan antara satu
dengan yang lain tidak akan menghasilkan qadhiyyah baru. Jadi untuk
memberikan hasil (konklusi) diperlukan beberapa qadhiyyah yang saling
berkaitan. Dan itulah yang namanya qiyas.
1. Qiyas Iqtirani
Qiyas iqtirani adalah qiyas yang mawdhu’ dan mahmul natijahnya berada
secara terpisah pada dua muqaddimah. Contoh: “Kunci itu besi” dan
“setiap besi akan memuai jika dipanaskan”, maka “kunci itu akan memuai
jika dipanaskan”. Qiyas ini terdiri dari tiga qadhiyyah; [1] Kunci itu
besi, [2] setiap besi akan memuai jika dipanaskan dan [3] kunci itu akan
memuai jika dipanaskan. Qadhiyyah pertama disebut muqaddimah shugra
(premis minor), qadhiyyah kedua disebut muqaddimah kubra (premis mayor)
dan yang ketiga adalah natijah (konklusi).
Natijah merupakan gabungan dari mawdhu’ dan mahmul yang sudah tercantum
pada dua muqaddimah, yakni, “kunci” (mawdhu’) dan “akan memuai jika
dipanaskan” (mahmul). Sedangkan “besi” sebagai had awshat.
Yang paling berperan dalam qiyas adalah penghubung antara mawdhu’
muqadimah shugra dengan mahmul muqaddimah kubra. Penghubung itu disebut
had awsath. Had awsath harus berada pada kedua muqaddimah (shugra dan
kubra) tetapi tidak tecantum dalam natijah. (Lihat contoh, pen).
Empat Bentuk Qiyas Iqtirani
Qiyas iqtirani kalau dilihat dari letak kedudukan had awsath-nya pada
muqaddimah shugra dan kubra mempunyai empat bentuk :
1. Syakl Awwal adalah Qiyas yang had awsth-nya menjadi mahmul pada
muqaddimah shugra dan menjadi mawdhu’ pada muqaddimah kubra. Misalnya,
“Setiap Nabi itu makshum”, dan “setiap orang makshum adalah teladan yang
baik”, maka “setiap nabi adalah teladan yang baik”. “Makshum” adalah had
awsath, yang menjadi mahmul pada muqaddimah shugra dan menjadi mawdhu’
pada muqaddimah kubra.
Syarat-syarat syakl awwal.
Syakl awwal akan menghasilkan natijah yang badihi (jelas dan pasti) jika
memenuhi dua syarat berikut ini:
a. Muqaddimah shugra harus mujabah.
b. Muqaddimah kubra harus kulliyah.
2. Syakl Kedua adalah Qiyas yang had awshat-nya menjadi mahmul pada
kedua muqaddimah-nya. Misalnya, “Setiap nabi makshum”, dan “tidak
satupun pendosa itu makshum”, maka “tidak satupun dari nabi itu pendosa”.
Syarat-syarat syakl kedua.
a. Kedua muqaddimah harus berbeda dalam kualitasnya (kaif, yakni mujabah
dan salibah).
b. Muqaddimah kubra harus kulliyyah.
3. Syakl Ketiga adalah Qiyas yang had awshat-nya menjadi mawdhu’ pada
kedua muqaddimahnya. Misalnya, “Setiap nabi makshum”, dan “sebagian nabi
adalah imam”, maka “sebagian orang makshum adalah imam”.
Syarat-syarat Syakl ketiga.
a. Muqaddimah sughra harus mujabah.
b. Salah satu dari kedua muqaddimah harus kulliyyah.
4. Syakal Keempat adalah Qiyas yang had awsath-nya menjadi mawdhu’ pada
muqaddimah shugra dan menjadi mahmul pada muqaddimah kubra (kebalikan
dari syakl awwal.)
Syarat-syarat Syakl keempat.
a. Kedua muqaddimahnya harus mujabah.
b. Muqaddimah shugra harus kulliyyah. Atau
c. Kedua muqaddimahnya harus berbeda kualitasnya (kaif)
d. Salah satu dari keduanya harus kulliyyah.
Catatan: Menurut para mantiqiyyin, bentuk qiyas iqtirani yang badihi
(jelas sekali) adalah yang pertama sedangkan yang kedua dan ketiga
membutuhkan pemikiran. Adapun yang keempat sangat sulit diterima oleh
pikiran. Oleh karena itu Aristoteles sebagai penyusun mantiq yang
pertama tidak mencantumkan bentuk yang keempat.
Qiyas Istitsna’i
Berbeda dengan qiyas iqtirani, qiyas ini terbentuk dari qadhiyyah
syarthiyyah dan qadhiyyah hamliyyah. Misalnya, “Jika Muhammad itu utusan
Allah, maka dia mempunyai mukjizat. Oleh karena dia mempunyai mukjizat,
berarti dia utusan Allah”. Penjelasannya: “Jika Muhammad itu utusan
Allah, maka dia mempunyai mukjizat” adalah qadhiyyah syarthiyyah yang
terdiri dari muqaddam dan tali (lihat definisi qadhiyyah syarthiyyah),
dan “Dia mempunyai mukjizat” adalah qadhiyyah hamliyyah. Sedangkan “maka
dia mempunyai mukjizat” adalah natijah. Dinamakan istitsna’i karena
terdapat kata ” tetapi”, atau “oleh karena”.
Macam-Macam Qiyas istitsna’i (silogisme) Ada empat macam qiyas
istitsna’i: Muqaddam positif dan tali positif. Misalnya, “Jika Muhammad
utusan Allah, maka dia mempunyai mukjizat. Tetapi Muhammad mempunyai
mukjizat berarti Dia utusan Allah”. Muqaddam negatif dan tali positif.
Misalnya, “Jika Tuhan itu tidak satu, maka bumi ini akan hancur.
Tetapi bumi tidak hancur, berarti Tuhan satu (tidak tidak satu)”. Tali
negatif dan muqaddam negatif. Misalnya, “Jika Muhammad bukan nabi, maka
dia tidak mempunyai mukjizat. Tetapi dia mempunyai mukjizat, berarti dia
Nabi (bukan bukan nabi)”. Tali negatif dan muqaddam positif. Misalnya,“Jika Fir’aun itu Tuhan, maka dia tidak akan binasa. Tetapi dia binasa,berarti dia bukan Tuhan”.
*
MEMPELAJARI ILMU MANTIQ
sebagai agama yang menjunjung tinggi akal, sangat menganjurkan
umatnya untuk mendidik dan membimbing akal. Tujuannya tidak lain agar
tidak terjerumus kedalam kesesatan berlogika.
Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah ilmu untuk menyelamatkan akal dari
kesesatan, yaitu Ilmu mantiq. Mantiq oleh sebagian kalangan disebut
sebagai bapak segala ilmu. Ini tidaklah berlebihan, mengingat mantiq
merupakan formula dan alat untuk menuju metode berfikir yang benar dan
jernih sehingga sampai kepada kesimpulan yang benar pula.
Imam al Akhdhari (1512-1575 M) dalam magnum opus nyaSullam Munawraq
mengungkapkan urgensitas ilmu mantiq:
و بعد فالمنطق للجنان ** نسبته كالنحو للسان
“Ilmu mantiq bagi akal ibarat ilmu nahu bagi lisan.”
Mantiq sebagai ilmu pertama kali disusun secara rapi oleh Aristoteles
(384-322 SM), seorang filosof Yunani. Ketika agama Islam telah tersebar
di Jazirah Arab dan dipeluk secara meluas sampai ke timur dan barat,
perkembangan ilmu pengetahuan pun mengalami kemajuan yang pesat.
Puncaknya terjadi pada masa pemerintahan Dinasti Abbasiyah. Di periode
inilah terjadi penerjemahan ilmu-ilmu filsafat Yunani kedalam bahasa
Arab, termasuk ilmu mantiq.
Dalam Islam, ilmu mantiq mulai di dilakukan oleh Al-Farabi, salah satu
filsuf Muslim yang sering dinyatakan sebagai maha guru kedua dalam ilmu
pengetahuan. Pada masa Al-Farabi ilmu mantiq dipelajari lebih rinci
dan dipraktekkan, termasuk dalam pentasdiqan qadhiyah.
Selain itu, para ulama juga semakin mendalami, menerjemahkan dan
mengarang karya bidang ilmu mantik. Di antaranya Abdullah Ibn
Al-Muqaffa’, Yaqub Ibn Ishaq Al-Kindi, Abu Nashr Al-Farabi, Ibn Sina,
Abu Hamid Al-Ghazali, Ibn Rusyd Al-Kuthubi.
Lantas, bagaimana hukum mempelajari ilmu logikamantiq ini? Bukankah
ia adalah ilmu baru dan berasal dari filosof Yunani?
Imam al Akhdhari menyebutkan hukum mempelajari mantiq dalam Kitab
Sullam Munawwraqnya:
و الخلف في جواز الإشتغال ** به على ثلاثة الأقوال
فابن الصلاح و النواوي حرما ** و قال قوم ينبغي ان يعلما
و القولة المشهورة الصحيحة ** جوازه لكامل القريحة
ممارس السنة و الكتاب ** ليهتدي به الى الصواب
Menurut perkataan al Akhdhari diatas bisa kita simpulkan bahwa hukum
mempelajari ilmuMantiq ada 3 :
Pertama, haram. Ini merupakan pendapat Imam Ibnu Shalah (643 H), dan
Imam An Nawawi (631-676 H).
Kedua, boleh mempelajari ilmu mantiq. Ini disandarkan pendapat
sebagian ulama, di antaranya Imam Abu Hamid Al Ghazali (450-505 H).
Beliau bahkan berkata, “Siapa saja yang tidak mengetahui mantiq, maka
ilmunya patut diragukan.”
Ketiga, apabila si pelajar mantiq mempunyai kecerdasan yang mumpuni,
pemahaman yang kuat, dan intelektual yang tinggi, serta mereka yang
memahami dan mengamalkan Al-Qur’an dan sunnah, maka boleh menyibukkan
diri dengan mantiq (mempelajarinya). Jika tidak demikian, maka tidak
boleh.
Tapi ada hal penting yang harus diketahui, bahwa ikhtilaf (perbedaan
pendapat) ulama-ulama di atas hanyalah pada mantiq yang disusupi
kalam-kalam dan kesesatan filsafat, seperti yang tertuang dalam kitab
Thawali’ul Anwar karya al Baidhawi (680 H).
Alasan diharamkannya mantiq yang seperti ini dikarenakan hal tersebut
mengikuti dan menyerupai Yahudi dan Nasrani. Dan juga ditakutkan akan
terjadi penyimpangan akidah bagi mereka yang mendalaminya, seperti kasus
kaum Mu’tazilah.
Syeikh Ibrahim al Bajuri (1783-1860 M) mengkritik pendapat di atas
dengan bijak. Beliau berpendapat, jika belajar mantiq haram dikarenakan
mengikuti Yahudi dan Nasrani, maka dengan sendirinya ilmu kedokteran
atau ilmu nahwu juga haram, karena Yahudi dan Nasrani juga mempelajarinya.
Nah, sebaliknya, jika mantiq yang dipelajari tidak tersentuh dengan
syubhat-syubhat filsafat, seperti kitab Mukhtashar karya al Sanusi,
Syamsiyah karya Abi al Hasan al Qazwini, Isagoji, Sullam Munawraq nya al
Akhdhari dan sebagainya.
Maka tidak ada alasan untuk mengharamkan ilmu mantiq. Para ulama telah
sepakat mantiqmodel ini boleh dipelajari. Bahkan hukumnya Fardhu
Kifayah jika harus digunakan untuk melawan syubhat-syubhat yang
ditujukan kepada agama Islam. Wallahu a’lam.
Sumber :
1. Al Bayan lima Yusghilul Azhan, Dr. Ali Jum’ah.
2. Idhahul Mubham Min Ma’aani Sullam, Ahmad Abdul Mun’im Damanhuri.
3. Hasyiyah al Bajuri ala Matnis Sullam, Syaikh Ibrahim al Bajuri.
HUKUM MEMPELAJARI FILSAPAT DAN MANTIQ
Filsafat terbagi dua:
PERTAMA
filsapat ahlu sunah waljama’ah.hukum mempelajarinya fardhu
kifayah,sperti mempelajari kitab sulamul munawaroq atau syamsiyyah dll.
KEDUA
Filsapat sesat yg kemudian banyak dianut oleh golongan mu’tazilah.
Yang dibahas berikut ini adalah hukum mempelajari filsapat yang kedua.
Dalam kitab “ I’anatuth tholibin juz 2 halaman47 :
ﻛﺎﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﻭﻫﻢ ﻣﻨﻜﺮﻭ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭﻋﻠﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰﺑﺎﻟﺠﺰﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻌﺚ ﻟﻼﺟﺴﺎﻡ ﻭﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻫﻲ ﺃﺻﻞﻛﻔﺮﻫﻢ
“Filosof adalah orang-orang yang mengingkari hudus alam,mengingkar i
ilmunya allah dengan juziyyah,dan mengingkari kebangkitan dengan
tubuh,dan 3 masalah inilah yang menjadi asal kekafiran mereka”
Dan imam sanusi sangat mewanti-wanti,dan memberi peringatan kepada
orang- orang yang baru belajar agar jangan mengambil ushuluddin dari
kitab-kitab yang bercampur dengan kalam falsafah,berikut ini perkatan
beliau :
ﻭﻟﻴﺤﺬﺭ ﺍﻟﻤﺒﺘﺪﻱ ﺟﻬﺪﻩ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﺃﺻﻮﻝ ﺩﻳﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺐﺍﻟﺘﻲ ﺣﺸﻴﺖ ﺑﻜﻼﻡ ﺍﻟﻔﻼﺳﻔﺔ
“hendaklah orang yang baru belajar menghindari kesungguhannya mengambil
ilmu ushulluddin dari kitab- kitab yang bercampur dengan perkataan
filsafah”Bahkan bukan hanya ilmu ushulludin yang bercampur dengan
filsafah saja yang di wanti-wanti untuk dihindari,juga ilmu mantiq.
Bahkan iman nawawi dan ibnu shalah mengharamkan mempelajari ilmu mantiq
yang bercampur dengan filsafah,sepert i yang disinggung oleh Abdurrahman
al- ahdhari dalam kitab Sulamul Munawwaroq
ﻭﺍﻟﺨﻠﻒ ﻓﻲ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻹﺷﺘﻐﺎﻝ >> ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ
ﻓﺎﺑﻦ ﺍﻟﺼﻼﺡ ﻭﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﺣﺮﻣﺎ >> ﻭﻗﺎﻝ ﻗﻮﻡ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥﻳﻌﻠﻤﺎ
ﻭﺍﻟﻘﻮﻟﺔ ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ >> ﺟﻮﺍﺯﻩ ﻟﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﻘﺮﻳﺤﺔ
ﻣﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺏ >> ﻟﻴﻬﺘﺪﻱ ﺑﻪ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ
“ terjadinya perbedaan wacana( antara para ahli) tentang status hukum
kebolehan memperdalam ilmu retorika qurani (ilmu mantiq logika),dapat
diklasifikasika nmenjadi tiga,yaitu Pertama,ibnu shalah dan imam nawawi
berpendapat haram,dan (kelompok yang kedua) sebagian kelompok ulama
mengatakan ilmu ini sebaiknya diketahui,dan pendapat(ketiga ) yang
terkenal menyatakan bahwa memperdalam ilmu retorica qurani (mantiq)
adalah shahih (benar) bagi mereka yang memiliki kesempatan
bernalar,berakal,yang mengerti seluk beluk hadits dan qur’an,yang
menguasai betul hadits dan al-qur’an.hal ini supaya mereka yang bernalar
logis bisa memperoleh petunjuk dari ilmu retorica ( mantiq) sampai pada
kebenaran yang hakiki.
Kesimpulannya :
Hukum mempelajari ilmu mantiq terbagi tiga:
1.Haram,menurut Imam Nawawi dan Ibnu Sholah.
2.Sunah menurut jam’un (diantaranya Imam Al-Ghozali).
3.Boleh atau Jawaz menurut qoul masyhur.Namun hukum Jawaz mempelajarinya
bagi orang yg punya nalar dan cerdas,dan bertujuan memperdalam hukum
syar’i (qur’an dan hadits).
Wallahu a’lam.




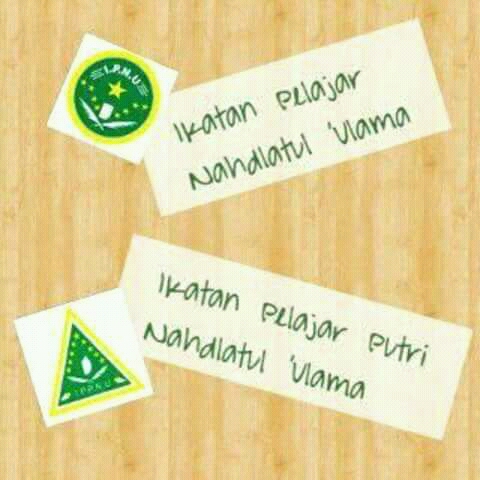


0 Komentar